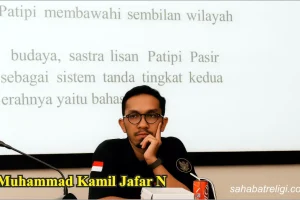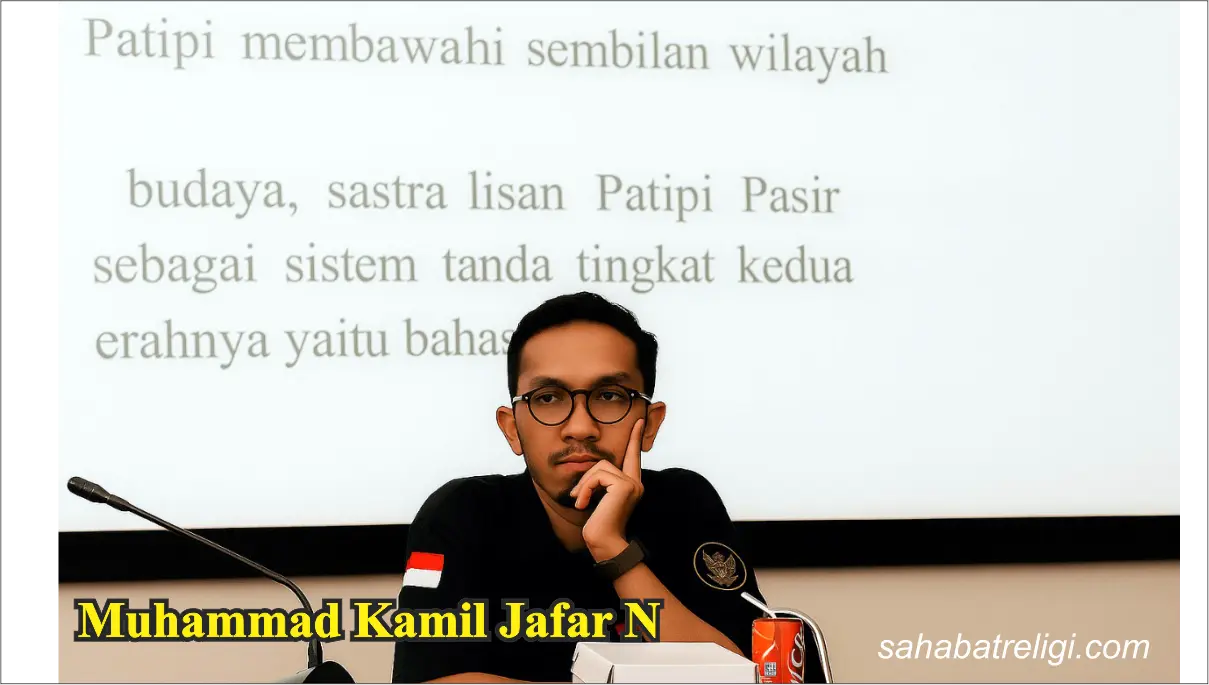Berdasarkan argumentasi logis dan akademis di atas, dapat dipahami bahwa istilah hukum Islam yang hanya disinonimkan dengan istilah fiqh sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan para ‘ulamā’ dan termaktub di dalam kitab-kitab mereka dan kemudian “dipaksakan” untuk menjadi istilah baku dalam memaknai istilah hukum Islam, dirasa tidak pas, karena definisi fiqh tersebut jika ditinjau melalui pendekatan universalitas hukum, maka sudah tidak lagi merangkum syarat dari sebuah definisi, yakni jāmi’ dan māni.
Kalimat yang tidak lagi dirasa jāmi’ adalah al-aḥkām asy- Syar’iyyah, dan yang tidak lagi dirasa sebagai māni’ adalah min adillatihā at-tafṣīliyyah. Jika ditinjau dari sifat hukum yang universal, dan dapat diaktualisasikan di seluruh penjuru dunia sehingga melahirkan hukum yang ṣaliḥ li kulli zamān wa makān, maka kalimat al-aḥkām asy-syar’iyyah harus segera direvisi dengan semangat pencarian kebenaran secara substansial dan bukan kebenaran yang bersifat tekstual.
Hal tersebut akan berimplikasi pada studi fiqh yang semakin hidup dan progresif, yang berupaya untuk incorporate the contexts and the needs of modern Muslims (menggabungkan konteks dan kebutuhan Islam modern) menuju want to act to preserve the vibrancy and variety of the Islamic tradition [3] (keinginan untuk melestarikan semangat dan berbagai tradisi Islam).
Model progresif sesungguhnya mengetengahkan semangat pembaharuan di kalangan eksponen hukum Islam (al-mujtahīd), khususnya melalui jalur metodologis, demi menghasilkan produk hukum kontemporer yang acceptable di kalangan masyarakat. Untuk itu, berpikir progressive ijtihadist harus diarahkan agar dapat melakukan lompatan yang jauh melampaui apologia yang sering dikumandangkan oleh kaum tradisionalis ataupun modernis dan juga melampaui batasan-batasan yang dicanangkan oleh kaum neo-modernis.[4]
Inkulturasi Wahyu: Antara Sumber Asasi, Ijtihad, dan Budaya Lokal
Pluralitas sosial-budaya dan politik di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam pertimbangan hukum demi lahirnya pembaharuan hukum yang responsif. Hal ini dapat ditemukan dari berbagai literatur klasik yang menggambarkan kebutuhan para ulama terhadap sosial-budaya dan politik sebagai sebuah pendekatan dalam melahirkan produk-produk ijtihad mereka.[5]